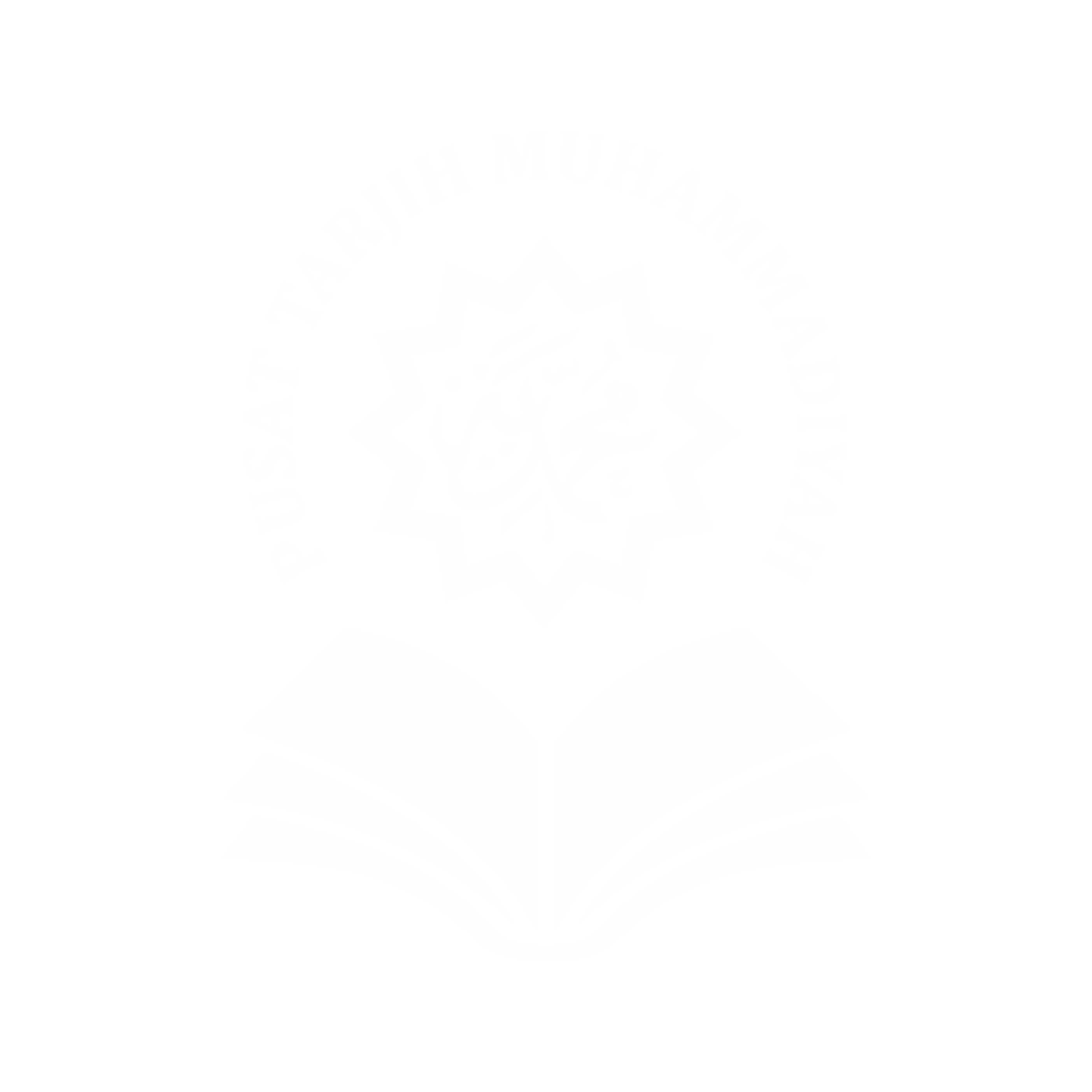Catatan Penting Delegasi Pusat Tarjih Muhammadiyah di Acara Intellectual Youth Summit 2.0
Penulis: Ilham Ibrahim
Pusat Tarjih Muhammadiyah ikut andil dalam rangkaian kegiatan Intellectual Youth Summit 2.0 (IYS 2.0) dengan mengirimkan dua delegasinya yakni Ilham Ibrahim dan Fadhlurrahman Rafif Muzakki. Acara yang berlangsung dari tanggal 16 s/d 17 Februari 2019 ini diselenggarakan di area kampus Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Diinisiasi dari berbagai ormas seperti Majelis Ulama Muda Indonesia (MIUMI), IYS 2.0 mengusung tema “Membangun Insan Cendekia Melalui Tradisi Ilmu dan Jejaring Komunitas” dengan harapan meraup dukungan akademis dari kalangan millenial akan pentingnya Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai pondasi peradaban.
Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan tawaran penting mengingat semakin menguatnya dualisme dan dikotomis ilmu yang membelah pengetahuan religius dan umum. Dualisme dan dikotomis ilmu tersebut merupakan anak kembar dari rahim ibu yang bernama sekularisme. Dalam sejarahnya, sekularisasi ilmu pengetahuan mula-mula pada ilmu alam kemudian pada ilmu-ilmu sosial dan memasuki ilmu-ilmu agama. Setelah sekularisme bersentuhan dengan agama, lahirlah apa yang disebut dengan religious studies, Islamic studies, dan comparatif study of religion. Istilah-istilah tersebut menuntut adanya sikap kritis-historis dalam melakukan pengkajian agama.
Sekularisasi terhadap ilmu-ilmu agama yang digalakan di Barat dilakukan karena mereka beranggapan bahwa masyarakat luas maupun civitas akademik masih terbebani dengan misi keagamaan yang bersifat memihak, subjektif, dan romantis, sehingga menghambat jalannya ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada akhirnya, sekularisme yang merupakan produk otentik peradaban Barat harus dilawan dengan Islamisasi ilmu pengetahuan. Akan tetapi menurut beberapa ahli yang tidak setuju dengan gagasan tersebut semacam Fazlur Rahman dan Kuntowijoyo, mengemukakan bahwa para pembawa ide Islamisasi ilmu pengetahuan tidak mampu mengembangkan metodologi apapun untuk menegaskan posisinya, selain berusaha membedakan Islam dari Barat.
Anggapan Fazlur Rahman dan Kuntowijoyo di atas kemudian dibantah oleh Syamsuddin Arif ketika menyampaikan materi tentang ‘Studi Evaluatif Implementasi Islamisasi Ilmu’ di Intellectual Youth Summit 2.0. Peneliti senior INSISTS ini mengungkapkan bahwa lontaran-lontaran kritik terhadap pemikiran-pemikiran Barat bukan untuk mencari perbedaan, atau membentuk identitas yang ‘penting bukan Barat’, melainkan untuk menunjukan suatu tantangan pemikiran Islam kontemporer. Sebab menurut Naquib al-Attas yang dikutip oleh Syamsuddin, ilmu pengetahuan yang sekarang sedang berjalan ini kehilangan tujuan yang sebenarnya karena disusupi semangat eksploitasi dan kekuasaan sehingga harus ‘diislamkan’.
Sebelum melakukan tawaran ide Islamisasi ilmu, Syamsuddin mengemukakan beberapa sarjana Barat semacam Jurgen Habermas dan Thomas Kuhn yang menegaskan bahwa ilmu pengetahuan itu sesungguhnya tidak netral dan tidak bebas nilai. Dengan mengutip Habermas, Syamsuddin ingin memperlihatkan bahwa manusia tidak memperoleh pengetahuan baru berdasarkan suatu hubungan netral terhadap realitas. Artinya, acapkali ditemukan pengetahuan baru, pasti didorong suatu tuntutan atau kepentingan-kepentingan tertentu dari kenyataan. Dengan mengutip Kuhn, Syamsuddin juga ingin menunjukan bahwa penemuan pengetahuan selalu disetir oleh nilai-nilai subyektif yang melekat pada seseorang. Artinya, suatu pandangan dapat dipengaruhi oleh latar belakang ideologi, suku, agama, relasi kuasa (otoritas), dan fanatisme mendasar tentang apa yang menjadi inti persoalan suatu ilmu.
Syamsuddin juga mengutip kritikan pemikir feminis kontemporer yang mempermasalahkan sains modern karena dianggap tidak terlalu adil terhadap perempuan. Anggapan bahwa ilmu pengetahuan harus netral ternyata merupakan pandangan yang keliru. Hal tersebut dijelaskan lebih konkret oleh Theodor Adorno yang menunjukan sikap intelektual yang kritis terhadap gagasan pencerahan di Eropa yang menurutnya mengalami kebuntuan. Adorno menyampaikan kritik terhadap pendekatan ilmu sosial Barat yang positivistik. Hal ini memberi dampak pada hasrat manusia yang lebih mementingkan kemajuan teknologi dan rasionalisasi. Akibatnya, muncul segregasi kepemilikan sumber daya alam. Pihak yang berkuasa atau pemilik modal pada saat yang bersamaan tidak hanya merendahkan martabat manusia, tetapi juga mengambil alih kekuasaan terhadap alam. Sebagaimana yang dikutip Syamsuddin, Adorno menyatakan bahwa dahulu manusia sibuk memahami alam, sejak abad 17 mereka sibuk memanipulasi alam.
Karena itulah, berdasarkan temuan Habermas dan Kuhn yang menegaskan bahwa ilmu pengetahuan itu tidak netral dan tidak bebas nilai, kemudian dipertegas oleh pemikir feminis kontemporer dan Theodor Adorno yang menyimpulkan bahwa ilmu pengetahuan yang disusupi falsafah Barat telah mengarahkan manusia ke jalan yang salah, Syamsuddin Arif kemudian menawarkan gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Jika ilmu yang sekarang digeluti banyak orang secara diam-diam telah disusupi nilai-nilai Barat yang bertentangan dengan Islam, maka tawaran Syamsuddin Arif akan Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang masuk akal.
Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer yang diwacanakan oleh Syamsuddin merupakan ilmu pengetahuan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan dikembangakan dari Islamic worldview dalam ragam penafsiran dan konteksnya. Dengan demikian, Islsmisasi merupakan proses dan upaya Islam yang sejak awal mencangkup pemikiran, mekanisme, kultural dan seluruh aspek kehidupan dan disertai dengan penyeleksian yang berdasarkan pada Islam. Bagaimanapun juga, pentingnya persoalan ini sebagaimana Syamsuddin mengungkapakan bahwa Islamisasi ilmu merupakan identitas Islam sebagai agama dan peradaban.
Menurut Syamsuddin Arif, ada lima pendekatan dalam memahami Islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu: apologetik, historis, praktis, edukatif, dan filosofis.
Pertama, pendekatan apologetik. Tipe Islamisasi sains model ini menurut Syamsuddin paling menarik bagi sebagian ilmuwan dan kebanyakan kalangan awam, karena menjadikan al-Qur’an dan hadis sebagai justifikasi temuan ilmiah modern, terutama di bidang ilmu-ilmu alam. Dalam konteks membangun rasa percaya diri, sebagai hujjah kebenaran Islam dan medium memantapkan keimanan, pendekatan apologetik ini mungkin cukup bermanfaat. Tapi dalam kerangka menyusun bangunan ilmu pengetahuan yang kokoh, pendekatan ini kurang memberi nilai guna lantaran al-Qur’an dan Hadis terkesan mengekor pada temuan ilmiah modern. Untuk itu, Syamsuddin kurang setuju dengan pendekatan ini sebab virusnya masih berada dalam tubuh ilmu itu sendiri. Tokoh paling populer dalam hal ini adalah Maurice Bucaille, Harun Yahya, Zaghlul An-Najjar, Zakir Naik, dan lain-lain.
Kedua, pendekatan historis. Menurut Syamsuddin, pendekatan ini memandang Islam pernah berkontribusi besar dalam mengembangkan sains dengan nilai-nilai Islam di abad pertengahan. Mereka berpendapat bahwa perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan di Barat merupakan imbas dan terpengaruh oleh kemajuan yang terjadi di dunia Islam. Untuk menunjukan kemajuan sains dan teknologi Islam pada masa keemasannya, cukuplah kiranya menyebut nama-nama, seperti al-Kindi, al-Khawarizmi, ar-Razi, al-Farabi, at-Tabari, Ibnu Sina, Umar Khayyam, al-Ghazali, dan Ibnu Rusyd. Tak seorang pun, baik di Timur ataupun di Barat, yang meragukan kualitas keilmuan mereka. Oleh sebab itu Syamsuddin berpendapat bahwa jika dalam dimensi waktu tertentu Islam mampu memimpin peradaban dunia dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang dipadukan dengan nilai-nilai Islam, maka bukan satu hal mustahil apabila kegemilangan itu dibangkitkan lagi. Tokoh-tokoh yang populer dalam hal ini adalah Donald R. Hill, Edward S. Kennedy, Ahmad Y. Al-Hassan, dan lain-lain.
Ketiga, pendekatan praktis. Pendekatan ini berpandangan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan dapat diwujudkan melalui penciptaan teknologi yang berguna bagi masyarakat dengan dilingkari prinsip-prinsip maqashid syariah. Menurut Syamsuddin, pendekatan ini menyadarkan umat untuk bangkit melawan ketertinggalan dan mengambil langkah mengembangkan sains dan teknologi.
Keempat, pendekatan edukatif. Pendekatan ini menilai akar dari kemunduran umat Islam di berbagai dimensi karena dualisme sistem pendidikan (Budi Hardianto, 2010). Di satu sisi, sistem pendidikan Islam mengalami penyempitan makna dalam berbagai dimensi, sedangkan di sisi yang lain, pendidikan sekular sangat mewarnai pemikiran kaum Muslimin. Menurut Syamsuddin, mengatasi dualisme sistem pendidikan ini merupakan tugas terbesar kaum Muslimin pada abad ke-20. Dengan demikian, Islamisasi ilmu pengetahuan dengan tipe ini diwujudkan dalam bentuk mengubah kurikulum yang tidak bermuatan nilai-nilai Islam, penulisan ulang buku-buku referensi, dan penguatan para pengajar (dosen dan guru). Pendekatan ini secara aktif dilakukan oleh Ismail Raji al-Faruqi, Mohammad Ishaq, Nidhal Guessoum, dan lain-lain.
Kelima, pendekatan filosofis. Menurut Syamsuddin, ide atau gagasan Islamisasi ilmu muncul di dunia Islam dan menjadi wacana di kalangan intelektual Muslim sebagai hasil dari kritik para sarjana Muslim terhadap sifat dan watak ilmu-ilmu alam dan sosial yang bebas nilai masih bergulir hingga saat ini. Karena itu, pendekatan filosofis ini berusaha membongkar selubung aspek ontologi, epistimologi, dan aksiologi dari setiap ilmu pengetahuan, kemudian membuang unsur-unsur yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, lalu menyusun kembali sesuai dengan epistimologi Islam yang dipandu dengan Islamic worldview. Dengan demikian Islamisasi sains akan membuat umat Islam terbebaskan dari belenggu hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Pendekatan ini disebut-sebut sebagai konsep Islamisasi sains yang paling mendasar dan menyentuh akar permasalahan sains kontemporer. Tokoh yang menggunakan pendekatan ini di antaranya: Naquib al-Attas, Alparslan Acikgenc, Osman Abu Bakar, dan lain-lain.
Itulah pemaparan Syamsuddin Arif tentang Islamisasi ilmu pengetahuan di acara Intellectual Youth Summit 2.0. Sebagai delegasi Pusat Tarjih Muhammadiyah penulis sangat menikmati sajian beliau. Penulis semakin tercerahkan bahwasannya ilmu pengetahuan yang selama ini berjalan ternyata mengandung bau tak sedap dari pemikiran Barat. Berbagai bukti telah disajikan, tetapi tetap saja masih ada orang yang mengkhayal. Mereka yang berkhayal bahwa ilmu itu bebas nilai, memiliki kecenderungan memusuhi gagasan Islamisasi ilmu. Mungkin benar kata pepatah Arab klasik bahwa manusia itu adalah musuh dari apa yang tidak diketahuinya (al-nas a’da’u ma jahilu).